
Pergantian Supplier Bahan Pangan MBG Diduga Picu Keracunan di Sejumlah Daerah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digulirkan pemerintah sebagai upaya memperbaiki status gizi anak-anak sekolah, kini menjadi sorotan tajam usai muncul sejumlah kasus keracunan massal. Di Baubau, Sulawesi Tenggara, misalnya, sebanyak 37 siswa dilaporkan mengalami gejala mual dan pusing setelah menyantap menu MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa dapur MBG di sana baru saja mengganti supplier bahan baku yang rutin menjadi supplier lokal, yang diduga belum siap dalam standar produksi besar.
Kejadian serupa juga dilaporkan di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dalam kasus tersebut, dugaan kuat penyebabnya terletak pada penggantian pemasok ikan cakalang. Dadan menyatakan jika supplier lamanya sudah biasa menyuplai ikan cakalang dengan kualitas baik. Karena ingin memberikan ruang untuk nelayan lokal, supplier diganti. Namun, kualitasnya menurun.
Jumlah kasus keracunan MBG sepanjang Januari hingga September 2025 tercatat 75 kejadian, dengan total 6.517 siswa terdampak. BGN menegaskan bahwa sebagian besar kasus itu disebabkan oleh pelanggaran SOP (Standar Operasional Prosedur), termasuk pembelian bahan baku terlalu awal (H-4 atau lebih), dan jarak waktu antara proses masak dan pengiriman yang melebihi batas optimal (4 – 6 jam).

Problem Supply Chain dari Pergantian yang Terburu-buru
Pergantian supplier memang bisa menjadi langkah positif untuk memberdayakan sumber daya lokal. Namun dalam konteks MBG, transisi yang cepat tanpa verifikasi dan audit kualitas dapat menimbulkan risiko. Dalam kasus Baubau, Dadan menyebut bahwa supplier baru belum memiliki kapasitas sebanding dengan supplier sebelumnya, baik dari aspek kualitas maupun kesiapan produksi skala besar.
Distribusi pangan massal menuntut rantai pasok yang terintegrasi, aman, dan terpadu. Namun faktanya, banyak dapur MBG (SPPG) baru atau di daerah pedesaan yang belum berpengalaman menangani volume besar. Dalam suasana demikian, kesalahan kecil di bagian hulu (supplier) bisa berdampak besar di hilir (keracunan konsumen).
Alih supplier juga sering disertai kendala teknis, mismeasure kualitas ikan, penggunaan es tanpa pemantauan suhu, atau logistik pengiriman yang terlambat. Selain itu, pengawasan dari institusi pengawas seperti BPOM atau lembaga sertifikasi lokal belum menjangkau semua supplier baru.
Implikasi Kepercayaan & Kewajiban Pemerintah
Akibat kasus-kasus ini, kepercayaan publik terhadap program MBG menjadi terguncang. Sekolah, orang tua, hingga pemerintah daerah mulai menuntut agar bahan pangan yang disajikan benar-benar aman, bergizi, dan terverifikasi. Tidak cukup hanya mengandalkan niat baik, bukti audit dan transparansi menjadi tuntutan.
Pihak Ombudsman dan lembaga pengawas menyuarakan agar setiap supplier MBG harus memiliki audit kelayakan bahan pangan dan sertifikasi keamanan pangan. Tanpa itu, pergantian pemasok lokal bisa dipertanyakan.
Pemerintah pusat pun merespon. Kementerian Pertanian menyebut bahwa keberhasilan MBG tergantung pada rantai pasok pangan yang solid, dari produksi, pengolahan, hingga distribusi. Strategi seperti near-sourcing (mengambil bahan dari area lokal untuk mengurangi jarak distribusi) disoroti sebagai cara meminimalisir kerusakan selama transportasi.
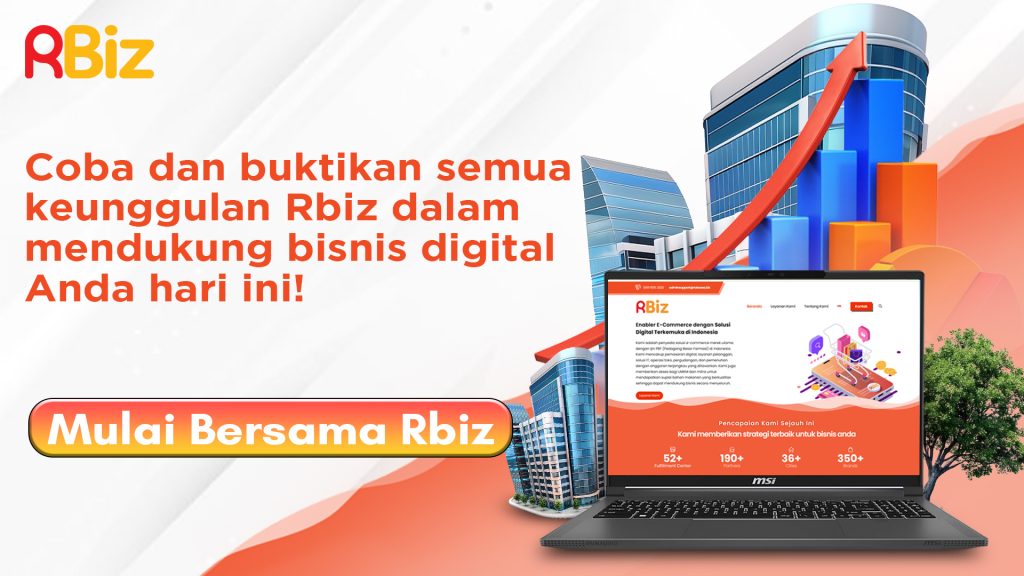
Peran Teknologi Transparansi Menuju Rantai Pasok Digital
Jika pergantian supplier bisa memicu keracunan, maka solusi tidak bisa hanya pada audit manual dan inspeksi khas. Di era teknologi, digitalisasi rantai pasok menjadi kunci utama untuk menjaga keamanan bahan pangan.
Sistem digital memungkinkan pelacakan (traceability) bahan pangan dari supplier hingga dapur penyaji. Data seperti tanggal panen, pemrosesan, pengiriman, suhu kendaraan angkutan, dan kode batch bisa direkam dan diverifikasi. Dengan cara ini, jika terjadi masalah, sumbernya bisa cepat ditelusuri.
Contoh nyata dari pelaku industri adalah Rbiz, platform e-commerce enabler Indonesia yang juga mendistribusikan bahan mentah berkualitas seperti sayuran segar, ikan, daging, dan rempah. Rbiz membangun jaringan pemasok dan logistik terintegrasi, sehingga pengguna atau lembaga bisa memverifikasi supplier dan kualitas bahan melalui dashboard digital.
Platform seperti itu cocok diterapkan dalam skema MBG setiap SPPG atau instansi pengelola bisa melihat “siapa supplier bahan baku”, “apa sertifikasinya”, dan “bagaimana jalur logistiknya”. Landing page transparansi berbasis data bisa menjadi titik rujukan publik dan pengawas independen.
Dengan adopsi sistem semacam Rbiz, pergantian supplier lokal tidak harus menimbulkan risiko mutlak. Asalkan sebelum mengganti, supplier baru sudah diverifikasi, diuji, dan ditautkan dalam sistem digital yang transparan.
Kesimpulan
Kasus keracunan MBG yang muncul di berbagai daerah menggarisbawahi bahwa masalah utama bukan hanya di dapur, tetapi jauh di hulu, yakni supplier bahan pangan yang belum siap disupervisi. Pergantian supplier secara terburu-buru, tanpa audit kualitas dan infrastruktur logistik mumpuni, menjadi bibit risiko.
Untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang, dibutuhkan pembenahan mendasar, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan pemain teknologi rantai pasok. Platform digital seperti Rbiz bisa dijadikan model integrasi dan transparansi rantai pasok pangan nasional.
Ketika sistem pengadaan pangan bergeser ke arah digital dan terbuka, maka niat mulia MBG, menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak, bisa terlaksana tanpa khawatir dampak keracunan. Inilah tantangan dan kesempatan reformasi pangan Indonesia, dari krisis menuju sistem pangan yang lebih aman, modern, dan dapat dipercaya.

